(11) - LOCKERS KENANGAN
Seperti
apakah hati perempuan itu seharusnya? Yang jelas tidak seputih kertas polos
atau sesederhana gaun terusan tanpa lengan. Hati perempuan ibarat labirin
dengan kotak-kotak tertutup yang bertumpuk di dalamnya. Jalan di tiap labirin
seperti benang kusut yang susah terurai. Setiap kotak pada ruangan hati ibarat
sebuah locker penuh barang. Ada yang
tersusun rapi, ada yang berserak. Setiap locker
menyimpan cerita. Setiap locker menyimpan kenangan-kenangan atau
rahasia-rahasia.
Febi
memegangi keningnya yang mengernyit. Tangan kanannya mencoret-coret selembar
kertas bertuliskan angka-angka. Neraca ini seharusnya seimbang, muridnya
membuat kesalahan dalam pengisian angka sehingga jumlah sisi kiri dan sisi
kanan tidak sama.
"Masih
lama, Bu?" Rekan seprofesinya, Bu Mutia, menegurnya. Febi tersenyum
sekilas dan mengangguk. Dia kembali menekuni tumpukan kertas dan angka-angka.
Dari
ujung matanya dia melihat Bu Mutia membereskan mejanya dan memasukkan
barang-barang pribadi ke dalam tas. Ini sudah waktunya jam pulang.
"Saya
duluan, ya, Bu." Bu Mutia berpamitan padanya dan meninggalkan Febi
sendirian di ruang guru.
Febi
meletakkan pena dan memandangi jam di dinding. Sudah pukul empat sore. Febi
tergoda untuk pulang dan segera berbaring meluruskan kaki dan melemaskan otot
punggung. Tapi dia tak ingin membawa koreksian anak didiknya ke rumah.
Pekerjaannya harus berakhir di sekolah dan rumah adalah tempatnya beristirahat.
Jika dia membawa pekerjaan ke rumah, sama artinya dia telah diperbudak oleh
pekerjaan. Tak ada waktu untuk kehidupan pribadi, tak ada waktu untuk
memikirkan dirinya yang masih lajang. Ibunya sudah sering mendesak agar dia
segera mencari suami. Tapi hatinya, pikirannya, tak pernah bisa menjalin
hubungan dengan pria lain. Dia masih mengharapkan pujaan hatinya, Ervan.
Dengungan
kecil dari dalam tas menarik perhatiannya. Febi menarik Zenfone-nya dari dalam
tas.
"Halo,
Dhit. Iya, aku masih di sekolah." Febi menumpuk kertas-kertas ulangan anak
didiknya.
"Persiapan
udah oke, Dhit. Sound system sudah
terpasang. Kursi-kursi juga sudah disusun. Kamu mau lihat? Oke, aku tunggu
sebelum jam lima, ya." Febi menutup telepon dan bergegas melanjutkan
mengoreksi.
Jam
lima lebih, Febi keluar dari kubikel dan berjalan dengan sedikit tergesa menuju
aula sekolah yang terletak di bagian belakang gedung SMA Harapan Bangsa.
Menyusuri deretan kelas 3 Fisika yang kini telah berubah menjadi kelas XII IPA.
Dibanding 20 tahun lalu, SMA Harapan Bangsa terlihat lebih hijau dan lebih
segar. Pohon-pohon perindang jauh lebih besar dan rimbun dibanding dulu.
Membuat suasana di depan kelas menjadi lebih teduh dan udara tidak terlalu
panas.
Febi
memperhatikan gedung aula yang terletak di belakang sekolah. Dulu, sebelum aula
dibangun, disitu ada lapangan basket dan lapangan bulu tangkis. Dia sering
mengamati Ervan yang berlarian menggiring bola, mengoper dan juga mengangkat
tubuhnya tinggi-tinggi agar bisa memasukkan bola ke dalam keranjang. Ada rasa
bahagia bila melihat Ervan berkeringat di lapangan. Dia seperti kuda Sumbawa yang
berlarian bebas di padang sabana.
"Hai!"
Seseorang menepuk pundak Febi. Dia melihat Adhit tersenyum padanya.
"Ingat
masa lalu?"
"Sedikit.
Kamu juga, kan?"
Adhit
terkekeh.
"Selalu.
Rasanya baru kemarin melihat dia terjatuh di lapangan lalu memapahnya ke
UKS."
"Kamu
..., rindu dia, ya, Dhit?" Febi menatap mata yang selalu redup di
hadapannya.
"Setiap
saat. Setiap saat, Feb." Adhit memandang Febi lekat-lekat.
"Kamu
tidak sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dariku, kan, Feb?"
"Maksudmu?"
Febi memandang Adhit tak mengerti.
"Ada
kabar apa dari Shila?" tanya Adhit menyelidik. Febi menunduk.
"Aku
tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, Dhit."
"Ya,
sudahlah. Aku juga tidak suka mendesak. Salahku juga dulu yang memintanya
menjauh dariku. Dia ..., dia pasti sangat terluka."
Adhit
menatap bangunan aula di hadapannya. Beberapa pekerja masih terlihat sibuk
mengatur meja dan kursi. Juga mengangkat pot-pot besar untuk diletakkan di
depan panggung.
"Oh,
ya, rasanya aku melihat Ervan di depan Supermarket Rita kemarin. Sayang aku
tidak sempat menyapanya. Beberapa teman sekelas kita juga sudah datang. Kemarin
kita berkumpul di Sido Roso."
"Kok,
aku nggak diajak?"
"Men only, Feb. Maaf." Adhit tertawa
ringan dan mengajak Febi masuk ke aula untuk melihat sejauh mana persiapan
untuk acara besok.
Sebagai
mantan ketua OSIS, tidak ada yang meragukan kemampuan Adhit dalam memimpin.
Termasuk memimpin panitia reuni 20 tahun angkatannya. Apalagi setelah
menyelesaikan kuliahnya di Teknik Industri UGM, Adhit lebih memilih mendirikan
perusahaan sendiri dari pada bekerja pada perusahaan-perusahaan bonafit. Dengan
dibantu orangtua Donna, istrinya, dan juga pinjaman finansial dari ayahnya,
Adhit merintis usaha dari skala kecil, CV. Dia mulai dengan proyek-proyek
bernilai kecil dan juga menjadi salah satu kontraktor perusahaan BUMN di
Cilacap. Berkat kerja keras dan kepandaiannya, kini usaha Adhit sudah merambah
ke bidang property. Dia membeli
sejumlah lahan di kawasan yang menurutnya potensial dan membangun unit-unit
rumah menengah ke atas. Adhit juga memiliki beberapa usaha ritel, penginapan
dan outshourching.
Febi
memandangi sosok Adhit yang sedang bercakap-cakap dengan salah seolah pekerja
di aula serba guna Harapan Bangsa. Dia mengarahkan kamera smartphonenya dan mengambil
beberapa gambar yang memperlihatkan sosok Adhit dengan jelas. Dia mengirimkan
foto-foto itu pada seseorang dan menuliskan beberapa kata.
‘Dia masih tetap
ganteng, kan?’
Pesannya
terbalas cepat disertai emo menangis.
‘Ya. Aku sempat
melihatnya di Rita kemarin.’
Febi
tersenyum membacanya. Shila telah mengunci kenangan tentang Adhit dalam salah
satu locker di ruang hatinya, 20
tahun silam. Selama itu, dia bersumpah tak akan pernah membukanya. Shila juga
berpesan agar Febi tidak pernah bercerita tentang Adhit jika tidak dia tanya.
Dia juga minta agar tidak menceritakan tentang dirinya kepada Adhit. Dan
meskipun ingin mulutnya berkata-kata, Febi tetap menjaga kepercayaan Shila
kepadanya.
Adhit
sering bertanya kabar tentang Shila, Febi selalu menjawab tidak tahu. Dia
memang tidak tahu. Shila hanya meninggalkan alamat surel untuk dihubungi.
Keluarga Shila pun bungkam ketika ditanya tentang kabar sahabatnya itu. Bahkan
ketika Shila menikah, Febi hampir tidak bisa menemui Shila. Shila datang tiga
hari menjelang ijab kabul dan segera meninggalkan keluarganya dua hari setelah
resepsi selesai digelar. Hanya dia teman Shila yang datang. Adhit tahu tentang
pernikahan Shila tapi dia menolak datang.
"Semua
sudah terlambat," katanya waktu itu. Dan dia benar, semua sudah terlambat.
Seandainya
Shila tidak mengunci lockernya begitu
rapat, kesempatan mereka untuk bersama lagi begitu besar. Tapi tidak ada yang
bisa mengalahkan takdir-takdir yang telah ditulis. Dan sepertinya, tidak ada
tertulis kata 'menikah' dalam takdir mereka. Seperti halnya tidak ada tertulis kata
'menikah' dalam takdirnya.
"Mengapa
kamu belum menikah, Feb?" tanya Shila sewaktu dia mengantarnya kembali ke
penginapan, setelah janji makan malam mereka.
Febi
terdiam mendengar pertanyaan yang selalu terlontar dari setiap orang yang
bertemu dengannya. Ya, mengapa dia belum menikah juga sampai umurnya hampir
kepala empat? Bukan karena tidak ada calon. Tidak. Febi bukan perempuan jelek
atau tidak sedap dipandang. Tubuhnya langsing, tinggi, kulitnya putih dan rambut
lurus yang halus memahkotai kepalanya. Jika bukan karena matanya yang lebar,
dia pasti mirip orang Cina.
Dia
pernah berpacaran serius beberapa kali dan pernah hampir menikah satu kali.
Tapi gagal. Semua hubungan itu kandas, karena hatinya yang begitu teguh
menyimpan satu nama yang dia percaya sebagai cinta sejatinya. Dia percaya suatu
hari nanti, takdir akan berbaik hati padanya dan mengizinkannya berbahagia
dengan lelaki cinta sejatinya.
"Siapa
dia, Feb?" Shila melanjutkan pertanyaannya ketika dilihatnya Febi tidak
menjawab pertanyaannya yang pertama.
"Maksudmu?"
"Aku
tahu dirimu. Kamu itu seseorang yang sangat teguh pendirian dan begitu fokus
pada tujuanmu. Kamu seorang pejuang yang tidak gampang menyerah. Kamu ingat
cerita kita tentang locker-locker di
ruang hati?" Febi mengangguk.
"Aku
menyimpan Adhit di salah satu locker
itu dan menyimpannya baik-baik saat aku menikah. Menguncinya rapat-rapat dan
mencoba melanjutkan hidup dengan harapan tidak pernah membuka locker itu lagi. Tapi locker itu ada di sana, Feb. Mengganjal
dan teronggok diam. Ya, locker itu
diam, tapi sangat mengganggu. Aku pernah meminta agar kamu membantuku membuat locker itu tetap mengunci."
Shila
memandang Febi yang masih tetap lurus memandang ke depan. Ke arah jalanan yang
terlihat lengang. Tangannya terlihat kaku memegang kemudi.
"Aku
salah. Locker itu tak bisa selamanya
terkunci. Karena itu membuat hatiku terasa berat. Kamu pasti tahu mengapa
akhirnya aku datang lagi ke sini setelah puluhan tahun? Aku ingin mengosongkan locker itu, Feb."
Mereka
berdua terdiam untuk waktu yang cukup lama, hingga mobil yang dikendarai Febi
berhenti di parkiran penginapan. Mereka berdua masih membisu memandangi deretan
paviliun-paviliun yang sebagian terlihat gelap. Ini bukan musim liburan sekolah,
hanya beberapa paviliun saja yang terisi. Gemericik air mancur penginapan
terdengar sayup-sayup di keheningan malam.
"Namanya
Ervan." Suara Febi memecah keheningan.
Shila
menatap riak muka Febi yang terlihat datar. Memandangi paviliun bertuliskan
nomor 12 seolah menanti penghuninya keluar dan menyapa mereka.
"Lelaki
itu. Lelaki yang aku nanti puluhan tahun, lelaki yang aku simpan di salah satu lockerku, namanya Ervan. Teman satu
sekolah kita. Kamu ingat?"
Febi
balas memandang Shila yang menatapnya dengan ekspresi yang susah dicerna.
Antara heran, tidak percaya, kecewa mungkin juga kesal.
"Ervan
anak basket?" tanya Shila akhirnya. Febi mengangguk.
“Ervan
anak basket.”
"Kok,
bisa?"
Akhirnya.
Pertanyaan tidak percaya itu muncul juga.
"Memangnya
kenapa?" tanya Febi, pura-pura heran. Padahal dia tahu apa yang dipikirkan
Shila.
"Yaaa
..., tahu sendirilah Ervan. Sok playboy dan sok beken. Buatku dia cukup
menyebalkan. Gimana ceritanya? Kalian sempat pacaran?" Shila menuntut
jawaban dari Febi.
"Dia
tidak seperti perkiraan kita, Shil. Dan tidak pernah ada pernyataan resmi kalau
kami pacaran. Tapi kami sangat dekat."
Febi
pun menceritakan segalanya tentang Ervan. Hubungan diam-diam mereka.
Kunjungan-kunjungan malam minggunya. Telepon-telepon mesra saat mereka berjauhan.
Email-email kerinduan dan puisi-puisi
cinta yang mengharukan.
"Tapi
Ervan pernah pacaran sama adek kelas, kan? Seingatku waktu kita kelas tiga.
Sempat heboh karena ternyata Nunu juga mengincar adek kelas itu. Ahh, aku lupa
siapa namanya. Kayaknya tinggal satu komplek denganku, deh."
Shila
terlihat berpikir keras, mencoba mengingat nama adik kelas pacarnya Ervan.
"Ningsih,"
kata Febi pendek.
"Ah,
ya! Itu. Ningsih!"
"Itu
cuma pengalihan, Feb. Ervan tidak sungguhan suka sama dia."
"Dan
waktu dia pacaran sama Ningsih, dia masih ngapelin kamu?"
"Untuk
sementara tidak. Ervan bilang, teman-teman mulai mencium hubungan kita. Makanya
Ervan jadian sama Ningsih."
"Kamu
tidak merasa aneh? Dia terang-terangan pacaran sama Ningsih, tapi
sembunyi-sembunyi tentang hubungannya sama kamu?"
"Dia
berusaha melindungiku, Shil. Menjaga perasaanku!"
"Menjaga
dari apa? Kamu yakin nggak sedang dimanfaatin sama dia?"
Febi
menggeleng. Menatap aneh pada Shila.
"Tidak
semua orang suka dengan hubungan terang-terangan seperti hubunganmu dengan
Adhit."
Suara
Febi begitu dingin menusuk saat mengatakannya. Membuat Shila sedikit terkesiap.
"Bu-bukan
begitu maksudku, Feb. Maaf." Shila membuang pandang dari Febi. Hubungannya
dengan Adhit, memang menjadi konsumsi warga sekolah. Semua anak selalu ingin
tahu segala sesuatu tentang mereka. Tepatnya, kapan mereka putus.
"Serius
banget ngelamunnya."
Suara
Adhit membawa Febi kembali pada kenyataan. Dia tersenyum samar.
"Dhit!
Seandainya ...," Febi menggantung kalimatnya. Mempelajari air muka Adhit
yang kini menatapnya.
"Seandainya
Shila datang, apa yang akan kamu lakukan?"
Febi
melihat Adhit menahan napas. (*)

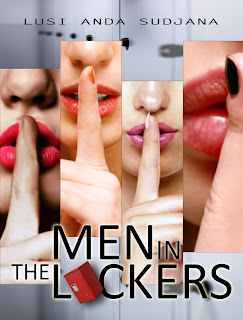

Komentar
Posting Komentar