(5) - PELANGI DEIRA
Mobil
Honda Jazz hijau melaju kencang. Menerobos lampu merah beberapa kali. Rodanya
berdecit-decit saat berbelok di jalan MT. Haryono. Siapa yang berani
menilangku? Hari ini hari Minggu, petugas patroli pun butuh istirahat. Aku pun mengurangi
kecepatan saat memasuki jalan Progo yang lebih kecil. Berhenti di depan pagar
besi yang tinggi. Membunyikan klakson beberapa kali, hingga seseorang keluar
tergopoh-gopoh dan membuka gerbang.
"Kelamaan
buka pintunya, Bik! Heran, deh, Mas Seto masih aja ngegaji Bibik yang udah peyot!
Nih, bawain bubur ayamnya, terus taruh di mangkuk. Jangan lupa bikinkan teh
manis. Panas, bukan hangat! Ingat!" Aku memelototi Bik Das. Dia selalu
salah membuatkan teh manis panas untukku. Entah karena dia sudah tua dan pikun,
atau disengaja agar aku kesal.
"Dari
mana pagi-pagi, Dek?" Mbak Lutik meletakkan teh manis yang baru
diseruputnya.
"Dari
lontong Pak Mul. Kangen sama bubur ayamnya. Ira beli lontong buat Mas sama
Mbak. Juga buat anak-anak dan Bik Das."
"Kenapa
repot-repot? Bik Das dah nyiapin mendoan anget dan sambel kecap buat sarapan.
Kesukaanmu." Mbak Lutik membantu Bi Das membuka bungkusan lontong dan
bubur, menuangkannya di mangkuk dan menatanya di meja.
"Mendoan
dan bubur bisa dimakan bareng, Mbak. Jangan kuatir. Tapi tolong bilang sama
Bibik pikun itu supaya bikin teh manis panas buatku yang bener. Panas. Bukan
anget!" Aku mengerling galak sama Bik Das yang terlihat tak acuh. Masih
sibuk menata sendok di meja.
"Heran,
kenapa Mbak sama Mas masih saja mempekerjakan dia," sambungku.
"Hush!
Bik Das itu dah puluhan tahun mengabdi. Dari zaman Mbak belum nikah sama Mas-mu
sampai sekarang. Susah cari orang bantu-bantu yang jujur kayak Bik Das."
Mba Lutik merangkul Bik Das dan tersenyum padanya.
"Sana
panggil, Mas Seto! Ajak sarapan, jangan ngurusi koi-nya terus." Mba Lutik
menyuruhku. Aku pun melangkah enggan ke halaman samping. Ke kolam koi milik Mas
Seto.
Di
rumahku di Semarang, tidak ada seorang pun yang berani menyuruhku melakukan ini
itu. Suamiku pun tidak. Dia lebih memilih menyuruh pembantu kami yang berjumlah
tiga orang ketimbang mengganggu aktifitas yang sedang kulakukan. Tapi di rumah
Mas Seto, adat berlaku. Sebanyak apa pun hartaku, setinggi apa pun derajatku,
tetap saja aku adalah adik bungsu Mas Seto. Aku harus mematuhi aturan Mas Seto
dan Mbak Lutik, harus nurut dan menghormati mereka.
Sebenarnya
aku enggan menginap di rumah mereka. Jika boleh, aku ingin menyewa kamar di
hotel saja. Tapi Mas Seto akan marah besar jika tahu aku pulang, tapi tidak
menginap di rumahnya. Apalagi rumah ini adalah rumah keluarga, yang diamanatkan
kepada Mas Seto sebagai anak sulung, sejak orang tua kami meninggal. Rumah ini
tempat kami, lima bersaudara, ngumpul tiap lebaran. Dan tempat kami merasa
memiliki kampung halaman. Ketiga kakakku yang lain, sama sepertiku, merantau ke
kota lain hingga ke pulau seberang.
Alasan
lain aku enggan tinggal di rumah ini, dan ini alasan paling penting, adalah aku
jadi sedikit terganggu mencari buruan. Selama dua hari di sini, belum sekali
pun aku keluar untuk berburu. Mas Seto tidak mengizinkan aku pulang terlalu
larut. Katanya, selama aku jauh dari suami, aku menjadi tanggung jawabnya. Ini
menyebalkan! Dan aku tidak bisa terlalu lama memendam hasrat berahiku. Aku
tidak mau harus memuaskan diri sendiri. Tidak! Selagi masih banyak lelaki yang
bersedia, kenapa aku harus mengotori tanganku?
"Mas?
Mas inget sama Kedasih, temenku yang dulu sering nginep di rumah?" tanyaku
saat sarapan. Mas Seto menghentikan kunyahannya dan berpikir sejenak.
"Yang
anaknya orang Pertamina itu? Ya, ya, kenapa? Apa kabarnya dia sekarang? Tinggal
di mana?"
"Dia
udah nggak di komplek lagi. Bapaknya udah pensiun, sekarang tinggal di Jalan
Perkutut."
"Oh."
"Mmhh
..., Ira boleh nggak nginep di rumah dia, Mas? Mau kangen-kangenan. Soalnya ada
temen yang baru datang dan nginep di rumah Asih. Kami pengen ngobrol puas dulu
sebelum acara reuni. Boleh, ya, Mas?" Aku menatap Mas Seto takut-takut.
Mas Seto terlihat berpikir sejenak.
"Masa,
nggak boleh,tho, Mas? Ira ini bukan anak kecil lagi. Anaknya udah dua..."
"Empat,
Mbak," ralatku cepat.
"Maksud,
Mbak ..., ya, empat. Tujuan dia kesini, kan mau reunian sama temennya. Ya, kasihlah
dia kebebasan sedikit."
"Aku
udah janji sama suaminya, Tik."
"Emangnya
Ira mau ngapain? Kamu nggak ada niat mau berbuat yang aneh-aneh, kan, Ra?"
Aku
menggeleng cepat.
"Ya,
sudah. Tapi kamu harus telepon suamimu. Pamit. Nanti kalau dia telepon, kan Mas
enak jawabnya."
Aku
mengangguk mengiyakan. Suamiku paling hanya akan bilang, hati-hati. Jaga diri.
Selamat bersenang-senang.
Aku
memang akan bersenang-senang. Aku juga tidak sepenuhnya berbohong. Lepas
Magrib, aku pergi ke rumah Asih. Berkumpul dan bercanda dengan yang lain.
Saling melepas rindu dan bercerita. Lalu jam sepuluh malam aku pamit keluar.
Kubilang ada janji mendadak. Sesungguhnya aku telah menemukan cara untuk
menuntaskan gairah yang meletup-letup seperti air yang bergolak. Dan aku sudah
bosan dengan obrolan yang saling mengenang pacar-pacar dan kisah cinta di SMA.
Sungguh! Aku muak! Karena kisah cintaku sendiri harus terputus hanya gara-gara
masalah sepele.
***
(23 tahun yang lalu)
Pelangi pelangi
Alangkah indahmu
Merah kuning hijau
Di langit yang biru
Pelukismu agung
Siapa gerangan?
Pelangi pelangi
Ciptaan Tuhan
Lirik
lagu itu seharusnya begitu. Tapi berubah saat dinyanyikan penggemar Deira.
Awalnya lagu itu dinyanyikan anak kelas dua, Akbar, saat Deira melintas di
hadapannya. Maksudnya, untuk menggoda dan menarik hati Deira, anak kelas satu
yang mirip boneka Barbie.
Deira Deira
Alangkah cantikmu
Merah kuning hijau
Kelopak matamu
Pelukismu agung
Siapa gerangan?
Deira Deira
Kucinta kamu
Lalu
lagu itu pun menjadi lagu wajib bagi para penggemar Deira. Menggaung di
mana-mana. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Mungkin juga dalam hati guru-guru
muda bujangan Harapan Bangsa. Akhir lagu itu juga seolah menjadi pernyataan
perasaan para penggemar tanpa harus mengatakannya dengan malu-malu dan takut
ditolak. Tapi Deira sangat pemilih. Tentu saja! Sebagai gadis tercantik sekelas
satu, dia berhak memilih yang terbaik. Dan dia memang ingin yang terbaik.
Sayang, yang terbaik sudah menjatuhkan pilihan pada gadis yang biasa-biasa
saja.
"Huh!
Apa bagusnya cewek itu, sih?"
"Kamu
suka Adhit juga?"
"Siapa,
sih yang enggak? Belum ada yang lebih ganteng dari dia, tau! Dia itu perpaduan
Adjie Masaid sama Onky Alexander."
"Onky
juga memilih cewek yang salah. Udah takdir kali, Ra, yang cantik dapetnya
jelek. Yang ganteng dapetnya jelek juga. Kamu juga jangan-jangan begitu."
"Kalau
gitu kenapa si Adhit nggak milih Hastuti aja. Dia, kan nggak ada duanya! Hahaha
..."
Tawa
Deira dan Lia, teman sebangkunya, berderai. Mereka sedang duduk di belakang
kelas 1-8 dan mengamati ke arah lapangan basket. Beberapa anak kelas satu dan
dua sedang adu memasukkan bola terbanyak ke dalam ring.
"Itu
siapa?" tunjuk Deira pada anak laki-laki yang sedang berkacak pinggang di
tengah lapangan.
"Ervan?"
"Bukannn!
Kalau Ervan aku tau yang mana. Itu, sebelahnya yang sekarang lagi
garuk-garuk."
"Oh,
Banyu? Anak paskibra kalau nggak salah."
"Oh,
pantesan. Badannya bagus. Keren. Putih. Nggak kalah dari Adhit."
"Kamu
suka, Ra? Sebaiknya nggak usah."
"Lho,
kenapa?"
"Soalnya
dia Kristen."
"Emang
kenapa kalau Kristen?"
"Yaaa
..., bedalah ama kita. Masa nggak tau?"
Deira
menggeleng.
"Aku,
kan bukan mau nikah ama dia. Masa cuma suka-sukaan aja nggak boleh."
"Yaaa
…, mana tau mau lanjut."
Deira
tersenyum sambil mengamati Banyu. Setia pada satu lelaki bukan prinsip dirinya.
Jika bisa menikmati banyak kenapa harus mencicipi satu?
"Bantu
aku dapetin Banyu, ya, Li."
Jalan
Deira meraih keinginannya kelewat mulus. Cowok mana yang bisa menolak pesona
Deira? Setelah dia dan Banyu sering terlihat berduaan di kantin, satu sekolah menjadi
geger. Banyak yang patah hati. Tidak sedikit yang menyayangkannya. Lagu wajib
pun berubah.
Deira Deira
Alangkah cantikmu
Merah kuning hijau
Celana dalammu
Pelukismu agung
Siapa gerangan?
Deira Deira
Kupatah hati
Deira
pun seperti menjilat ludah sendiri. Ternyata dia sangat terikat pada Banyu Arya
Pratama. Bukan saja karena Banyu sangat baik dan perhatian, tapi Banyu bisa
meredam darahnya yang selalu bergejolak. Dan dia ingin lebih. Lebih, lagi,
lagi, lagi, dan terpuaskan! Tapi Banyu selalu berhasil menahan. Dua tahun
hubungannya dengan Deira, hanya sebatas memegang, membelai dan mencium. Deira
tidak puas. Dia mau yang lain. Dia ingin yang lebih.
"Aku
mau lebih, Bee!" Rayu Deira manja.
"Dee,
kamu, kan udah tau jawabannya. Kita simpan buat saat istimewa nanti, ya?"
Banyu
membelai rambut Deira. Turun ke lengannya lalu berakhir di atas pahanya. Banyu
memandangi tubuh Deira yang setengah telanjang di atas kasurnya. Cantik sekali.
Seperti peri dalam buku-buku dongeng. Kulit Deira kekuningan. Rambutnya
kemerahan. Belum lagi bibir Deira yang merah muda dan selalu basah. Hidung yang
sangat mancung, alis mata tebal membingkai bola mata besar berbulu panjang dan
lentik. Tahi lalat menghiasi dagu Deira yang menggantung. Seperti Elvi
Sukaesih. Tubuhnya sintal, berisi. Tidak kurus seperti cewek-cewek kekurangan
makan. Banyu merasa beruntung. Apalagi Deira rela menyerahkan semua itu
padanya. Banyu menelan ludah. Dia masih laki-laki normal, tapi sekali menodai
Deira, dia harus siap menjalani segala akibatnya.
"Kamu
cinta aku, kan, Bee?" Deira membelai wajah Banyu. Dagunya. Lehernya. Dan
mengusapkan lima jarinya pada dada Banyu yang bidang dan telanjang.
Rumah
Banyu selalu kosong sebelum jam tujuh malam. Sepulang sekolah Banyu kerap
membawa Deira ke rumah dan mencumbunya. Terlalu sering, hingga membuat Deira
ketagihan.
"Kamu,
kan tau kalau aku cinta banget ama kamu, Dee."
"Kalau
gitu tunggu apalagi? Ayolah, Bee!" Deira menatap Banyu, memohon. Tangannya
menggenggam tangan Banyu di atas kasur.
Banyu
membalas tatapan Deira. Masih bimbang. Setan-setan membisikinya makin kuat.
***
Aku
memasuki bar yang katanya terkenal di kota ini. Jika benar, seharusnya dipenuhi
laki-laki segar yang bisa kuburu. Adrenalinku naik secara perlahan. Stilettoku
bergerak teratur ke arah bartender. Sambil memandang berkeliling sekilas dan
tersenyum menggoda kepada beberapa kandidat. Jika tepat sasaran, tidak lama
lagi mereka akan merubungiku seperti semut menemukan permen.
"Margarita
klasik," kataku pada bartender. Tak lupa aku tersenyum manis dan mengedip
padanya yang ... yahhh, 7 dari 10.
Sambil
menunggu minuman siap, aku memutar duduk dan mencoba menikmati live music di ruangan yang minim cahaya.
Mataku mengamati pengunjung satu per satu. Dan, di sana, di sudut ruangan yang
terhalang beberapa kepala, aku menemukan sepasang mata yang kukenal sedang
menatapku. Darahku berdesir-desir. Ribuan semut menggigiti kulitku. Napasku
cepat memburu.
Aku
menginginkannya! (*)
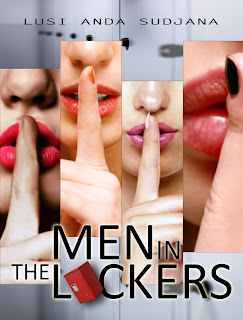

Komentar
Posting Komentar